Sebuah novel berjudul AMBA tentang gejolak 65 dan pulau Buru baru saja terbit. Inilah buku yang menurut pengarangnya, ingin menampilkan sejarah tentang orang-orang biasa yang dilindas arus kekerasan di Indonesia.
Sejarah kadang dan bahkan sering menempuh jalan tak terduga.
Apa yang terjadi setelah orde baru mengirim ribuan tahanan politik ke Buru? Pulau itu berubah: bukan komunisme tapi hamparan sawah. Dataran Waeapo yang dulu adalah tempat “permukiman“ para tapol, kini menjadi lumbung padi Maluku.
Lebih dari tiga dekade, orde baru mencekoki para pelajar tentang bahaya laten Komunisme. Hasilnya? Tidak melulu prasangka, meski tentu saja masih banyak orang Indonesia yang membaca 65 dengan kacamata orde baru. Tapi ada banyak pula orang dari generasi itu yang “melenceng“ dari cita-cita orde baru, paling tidak itu terjadi pada Laksmi Pamuntjak, yang baru saja menerbitkan novel “AMBA“.
Laksmi Pamuntjak, lahir pada tahun 1971, ketika tahanan politik atau tapol golongan ketiga tiba di pulau Buru. Dia lahir pada masa ketika anak-anak diajari mendaras versi sejarah 1965-1966 yang ditulis oleh sang pemenang: orde baru. Tragedi yang oleh dunia disebut sebagai salah satu pembantaian massal paling biadab di abad-20.
Bertahun-tahun, generasi saya hidup dengan versi sejarah yang sepihak dan normalisasi kejahatan. Begitu terus -- hingga bohong dan bungkam menjadi bagian dari watak kehidupan di Indonesia,“ kata Laksmi Pamuntjak kepada Deutsche Welle.
“Sebuah novel bukan untuk mengoreksi Sejarah. Saya hanya ingin mencipta ulang sejarah dengan huruf s kecil, tentang kisah-kisah manusia biasa yang tidak tercatat. Tentang mereka yang tidak terlibat, tapi hidupnya berubah dilimbur arus sejarah,“ kata Laksmi.
Deutsche Welle:
Mengapa anda menulis tentang 1965?
Laksmi Pamuntjak:
Mengapa TIDAK? Sekarang, hampir 48 tahun setelah tragedi itu, kita melihat kemunduran. 13 tahun setelah (Presiden-red) Gus Dur secara terbuka meminta maaf kepada para korban, dan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi tentang tragedi ini, sejumlah ulama NU malah menolak minta maaf dan meminta Presiden mengikuti jejak mereka. Menko Polkam Djoko Suyanto menolak hasil investigasi dan bersikukuh bahwa apa yang dilakukan militer pada waktu itu ‘benar' karena apa yang mereka lakukan adalah memburu “sang musuh negara.” Sementara rekonsiliasi masih jauh dari angan – generasi penerus akan semakin berjarak dari 65 dan berpikir tindakan seperti itu, human rights violations yang disponsori negara, sah dilakukan, karena toh itu sebuah tugas negara. Belum lagi, ada generasi baru yang sama sekali buta sejarah. Survey The Jakarta Globe tahun 2009 menunjukkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa Jakarta, sama sekali tak pernah mendengar tentang adanya pembantaian massal 1965-1966. Jadi, bagi saya, lebih banyak orang yang mengangkat tema 65 semakin baik!
Deutsche Welle:
Kenapa anda tertarik untuk menulis cerita tentang pulau Buru?
Laksmi Pamuntjak:
Yang jelas bukan untuk mengoreksi sejarah atau menafsirkan siapa yang bertanggungjawab atas pembantaian massal 65. Ketika menjalin persahabatan dengan eks tapol, saya melihat sejarah bukanlah sebuah narasi besar politik, atau Sejarah dengan S besar, tapi sejarah adalah kisah-kisah manusia biasa yang tidak tercatat. Novel membuka kemungkinan untuk menampung ruang-ruang kecil yang sering luput dari Sejarah. Saya merasa terpanggil untuk memanggil ulang ingatan kolektif, bagaimana memahami sejarah kelam di mana saudara dan tetangga saling membunuh. Masa ketika yang menguasai adalah praduga, amarah, dendam dan kebencian. Ketika mendengar kisah (tapol-red) Buru saya terharu, karena seiring derita, ketakutan, putus asa dan rasa sakit, masih ada humor. Kadang-kadang di antara mereka ada rasa syukur atas sebentuk kebaikan atau keindahan yang tak terduga-duga, sesuatu yang menolak dari dendam dan kebencian. Apa yang saya lakukan dengan berbagai bahan dan kenangan yang dibagi secara murah hati oleh mereka yang telah mengalami Buru adalah dengan mendengarkan mereka. Mencoba menyelami seperti apa rasanya diam dibungkam, memendam perasaan begitu lama. All the silences around you. Itu juga bagian dari duka itu sendiri. Sumber utama saya adalah Amarzan Loebis (wartawan senior TEMPO dan eks tapol-red) yang dikirim ke pulau Buru pada November 71. Juga kepada Hersri Setiawan dan Kresno Saroso, sebagai orang-orang yang pada siapa selain Pram, saya berhutang budi.
Deutsche Welle:
Ketika pertama datang ke pulau Buru, apa yang anda lihat?
Laksmi Pamuntjak:
Saya kaget, karena saya membayangkan begitu banyak hal menyeramkan. Tetapi ketika sampai di sana yang ada adalah padi di mana-mana. Kesuburan yang merupakan buah kerja keras dan keringat eks tapol yang membuka lahan dan menjadikan Buru sebagai mini Jawa. Tak ada lagi sisa Tefaat (Tempat Pemanfaatan istilah yang dipakai untuk pemukiman tapol-red), kecuali sebuah gedung kesenian yang kalau tidak diberi konteks bahwa ini bagian dari era itu, maka kita samasekali tidak mengerti nilai sejarahnya.
Deutsche Welle:
Dari karakter para tapol yang anda pelajari, apakah anda melihat para survivor ini berhasil ditundukkan oleh kekuasaan lewat pulau Buru?
Laksmi Pamuntjak:
Saya melihat ada perbedaan dari masing-masing survivor. Ada yang merasa bahwa mereka menang dengan tidak bersedia tunduk kepada kekuasaan dan mempertahankan harga diri dengan mengadakan berbagai ritual sendiri seperti mengubur surat-surat di dalam tabung bambu dan menyembunyikannya di bawah pohon. Mereka punya cara sendiri untuk melawan. Tapi ada hal menarik yang diungkapkan bekas Asbintal (Asisten Pembinaan Daerah Militer-red) yang juga bekas Kepala Pengawal di Tefaat Buru yang dikenal baik, berpikiran terbuka, dan sering membawa majalah TIME atau TEMPO bagi para tapol. Kami kebetulan bertemu, saat dia ingin mengadakan semacam reuni dengan eks tapol yang tetap tinggal di Buru. Asbintal itu bercerita, saat reuni, tiba-tiba para eks tapol ini berbaris dan body languagenya seperti orang-orang yang dikuasai. Padahal Asbintal ini, dulunya bukan simbol dari kekuasaaan yang paling buruk di pulau Buru…apalagi kini konteksnya berbeda karena para eks tapol ini sekarang manusia bebas dan setara (dengan Asbintal-red), jadi the power game-nya sudah berubah. Tapi body language para eks tapol begitu kental, seperti lapis kulit kedua. Mereka kembali ke insting-insting lama. Jadi sulit mengatakan apakah para survivor Buru ini menang atau kalah. Saya selalu menyadari, bahwa saya menulis tentang sebuah masa lalu yang bukan merupakan “masa lalu” saya. Apapun empati yang tercakup dalam novel, tak pernah akan bisa mereplikasi penuh emosi yang terkandung dalam pengalaman para survivor.
Deutsche Welle:
Saat membaca AMBA saya membayangkan Zulfikar adalah Amarzan Loebis. Apakah karakter dalam novel ini terinspirasi dari orang-orang dekat anda?
Laksmi Pamuntjak:
Secara tipe mungkin ya. Misalnya saya selalu bisa membayangkan dengan mudah siapa orang yang senang membaca seperti karakter Bhisma (yang di dalam novel adalah kekasih AMBA-red). Orang-orang yang selalu mengalami dilema dan tidak pernah bisa berpihak. Tidak pernah belonging. Dia selalu berada di tengah-tengah dan selalu gelisah mengenai ide-ide dan kenyataan di depan batang hidungya. Tapi di antara karakter yang paling kental memang Zulfikar.
Deutsche Welle:
Menurut anda, apa yang membedakan anda dengan Pramoedya Ananta Toer dalam melihat tragedi 65?
Laksmi Pamuntjak:
Sulit ya… karena dia (Pram-red) terlibat. Sementara saya bisa menulis AMBA justru karena berjarak, dan menggunakan pengalaman orang seperti Pram sebagai titik tolak untuk memahami 65. Ego atau ke-Aku-an saya tidak besar, karena (AMBA-red) tidak datang dari sudut pandang saya sendiri. Soal style beda, karena dasarnya saya punya tempramen puitis. Saya juga selalu suka apa yang tidak hitam putih, yang selalu di tengah-tengah, yang remang-remang. Mungkin itu juga yang membuat saya menulis tentang 65, karena itu adalah episode sejarah kita yang remang-remang tapi selalu dihitam-putihkan.
- anggal 19.02.2013
- TPenulis Andy Budiman
- Editor Christa Saloh-Foerster
- Bagi artikel Kirim Facebook Twitter google+ lainnya
- Feedback: Tulislah kepada kami!
- Cetak Cetak halaman ini
- Permalink http://dw.de/p/17ejB

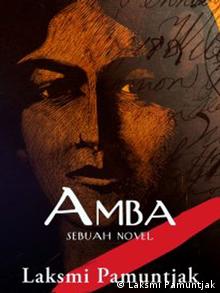


 Dibaca:
Dibaca:  Komentar:
Komentar:  1 aktual
1 aktual